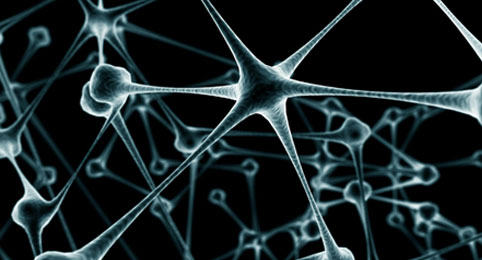This is default featured post 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured post 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured post 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured post 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured post 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Sabtu, 13 Oktober 2012
Selasa, 06 Desember 2011
Desersi (kejahatan militer terhadap tugasnya)
Desersi (kejahatan militer terhadap tugasnya)
A. Pengertian Desersi dan Macam-Macam Tindak Pidana Desersi
Menurut kamus bahasa Indonesia desersi adalah (perbuatan) lari meninggalkan dinas ketentaraan; pembelotan kepada musuh; perbuatan lari dan memihak kapada musuh.
Pengertian atau definisi dari desersi tersebut dapat disimpulkan dari pasal 87 KUHPM, bahwa desersi adalah tidak hadir dan tidak sah lebih dari 30 hari pada waktu damai dan lebih dari 4 hari pada waktu perang. Ciri utama dari tindak pidana desersi ini adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat dan waktu yang ditentukan baginya dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas.
Dalam perumusan pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam jenis tindak pidana desersi yaitu :
1. Tindak pidana desersi murni diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM.
2. Tindak pidana desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin, diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 dan ke-3 KUHPM.
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Desersi
Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tindak pidana desersi. Adapun tindak pidana desersi ini diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berbunyi :
1. Diancam karena desersi, Militer :
Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, dihindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
Ke-2, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;
Ke-3, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karena tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintah.
2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.
Apabila kita cermati substansi rumusan pasal tersebut, sesuai dengan penempatannya dibawah judul mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, maka dapat dipahami bahwa hakekat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer.
Sikap tersebut dapat saja terealisasikan dalam perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamanya.
Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana ia harus berada, tanpa itu sukar dapat diharapkan dari padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya.
Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer.
Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi.
Apabila kita mencermati makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, secara sepintas perbuatan tersebut, menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali lagi ketempat tugasnya.
Mungkin saja hal ini dapat dilihat dari suatu kenyataan bahwa ia telah bekerja pada suatu perusahaan, tanpa menyatakan pekerjaan tersebut hanya bersifat sementara.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hakikat dari tindak pidana desersi, bukan hanya sekedar perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam tenggang waktu tiga puluh hari. Melainkan harus di maknai bahwa hakikat dari perbuatan desersi tersebut, terkandung maksud tentang sikap dan kehendak pelaku untuk menarik diri dari kewajiban dinasnya dan karenanya harus ditafsirkan bahwa pada diri prajurit tersebut terkandung kehendak atau keinginan bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk tetap berada dalam dinas militer. Hal ini harus dipahami oleh para penegak hukum dilingkungan TNI, khususnya para hakim militer agar dalam memeriksa dan mengadili perkara desersi dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan kesatuan militer.
Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataan, sering terjadi motivasi seorang prajurit melakukan desersi, dikarenakan rasa takut kepada seniornya akibat suatu kesalahan, sehingga ia memilih untuk pergi meninggalkan dinas karena apabila ia ada di kesatuan akan menghadapi tindakan keras dari seniornya. Hal lainnya adalah dikarenakan banyak hutang disana-sini sehingga ia lebih memilih pergi meninggalkan kesatuan ketimbang menyelesaikan masalahnya itu, dan banyak juga motivasi lainnya.
Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana desersi ada 2 macam yaitu:
1. Faktor ekstern meliputi :
a. Perbedaan status sosial yang mencolok
b. Terlibat perselingkuhan/mempunyai wanita idaman lain (WIL)
c. Jenuh dengan peraturan/ingin bebas
d. Trauma perang
e. Mempunyai banyak hutang
f. Silau dengan keadaan ekonomi orang lain
2. Faktor intern meliputi :
a. Kurangnya pembinaan mental (Bintal)
b. Krisis kepemimpinan
c. Pisah keluarga
Untuk mencegah terjadinya perkara tindak pidana di lingkungan TNI, maka setiap satuan hendaknya :
1. Meningkatkan efektifitas pengawasan melekat atau pengawasan internal sebagai salah satu fungsi komando.
2. Melaksanakan program pembinaan personel dan pembinaan mental untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan prajurit terhadap ajaran agama, etika dan moral serta peraturan hukum dan tata tertib.
3. Mengadakan evaluasi faktor penyebab terjadinya perkara, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.
4. Menindak tegas prajurit TNI yang terlibat perkara pidana dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menghindarkan proses penyelesaian yang berlarut-larut.
C. Hambatan Penyelesaian Perkara Desersi Ciri utama tindak pidana desersi ditunjukkan dengan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin seorang militer pada suatu tempat yang ditentukan baginya, dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas.
Diluar organisasi militer, perbuatan ketidakhadiran ini tidak ditentukan sebagai suatu kejahatan, tetapi dalam kehidupan militer ditentukan sebagai kejahatan dan kepada pelakunya apat dijatuhi pidana penjara bahkan sampai pemidana-an yang paling berat yakni penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer. Pemberian sanksi tersebut, sesuai dengan hakikat dan akibat dari tindak pidana desersi, dimana kesatuan yang bersangkutan tidak dapat mendayagunakan tenaga dan pikiran personel tersebut untuk melaksanakan tugas pokok.
Pelaksanaan persidangan tindak pidana desersi sering menemui hambatan dikarenakan pelakunya tidak kembali atau tidak berhasil ditangkap sehingga Terdakwa tidak bisa dihadirkan di persidangan. Akibatnya terjadi tunggakan penyelesaian perkara, dan bagi kesatuan dapat berpengaruh terhadap pembinaan satuan dan pencapaian tugas pokok satuan.
Dalam praktek peradilan, tindak pidana tersebut kerap menimbulkan kesulitan antara lain yang berkenaan dengan penentuan locus dan tempos delicti yang ada kaitannya dengan kompetensi pegadilan misalnya: seorang Kapten X anggota Kodam A mendapat perintah untuk mutasi ke Kodam Jayapura. Yang bersangkutan berdasarkan surat perintah dari Pangdam A, telah melapor kepada atasannya untuk melaksanakan perintah mutasi ke Kodam Jayapura.
Namun dalam kenyataannya, Kapten X tidak segera berangkat ke Kodam Jayapura, baru setelah lewat waktu enam bulan, Kapten X berangkat ke Jayapura dan melapor kepada Komandan Satuan di Kodam Jayapura. Selanjutnya Kapten X oleh Atasannya diserahkan kepada Penyidik Polisi Militer, karena diduga tidak hadir tanpa izin lebih lama dari 30 hari.
Persoalan yang timbul dari posisi kasus tersebut adalah; apakah ia diduga melakukan desersi, dimana locus delicti dan sejak kapan menentukan awal tempos delictinya, atau apakah melakukan tindak pidana insubordinasi (pembangkangan terhadap perintah dinas, karena tidak melaksanakan perintah mutasi/pindah kesatuan ke Kodam Jayapura). Dilihat dari sudut tugas dan kewajiban Kapten X untuk berada dikesatuan guna melaksanakan tugas kewajibannya sebagai Perwira di Kodam Jayapura, maka kepadanya dapat diterapkan tindak pidana desersi. Tetapi apabila penekanannya terhadap pelaksanaan surat perintah yang dikeluarkan Kodam A untuk melaksanakan mutasi, ternyata ia tidak melaksanakannya atau melaksanakan dengan semaunya, maka kepadanya dapat diterapkan pembangkangan atau insubordinasi. Demikian pula dari aspek tempos, sejak kapan Kapten X melakukan ketidakhadiran, apakah setelah yang bersangkutan melapor kepada atasannya di Kodam A. Untuk penerapan tindak pidana desersi, penentuan tempos ini perlu diperhatikan karena untuk menentukan lama ketidakhadiran seorang prajurit di kesatuan. Demikian pula, harus ditentukan dimana kesatuan yang ia tinggalkan, karena yang bersangkutan belum melapor ke tempat satuan baru.
Kesulitan dalam praktek untuk menghadirkan para pelaku tindak pidana desersi ke muka sidang, telah disadari oleh pembuat Undang-undang, karenanya pembuat Undang-undang telah merumuskan secara limitatif dalam sebuah pasal untuk menyidangkan perkara desersi secara in absensia.
1. Persidangan perkara desersi secara in absensia
Ketentuan ini dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dirumuskan dalam beberapa pasal, yakni:
a. Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: “Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara”.
Substansi dari rumusan pasal 124 ayat (4) tersebut:
1) Bahwa pemeriksaan Tersangka bukan merupakan syarat formal
2) Pemberkasan perkara desersi yang dilaporkan oleh Satuan kepada Penyidik dapat dilakukan meskipun Tersangka tidak ada.
Dengan demikian dari substansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana desersi ini dilakukan tanpa hadirnya Tersangka, karenanya dinamakan penyidikan perkara desersi in absensia.
Kemudian terhadap berkas hasil penyidikan ini akan disidangkan secara in absensia. Ketentuan formalitas tersebut terdapat permasalahan, yakni mengenai penentuan tempos delicti, yaitu sampai kapan waktu desersi tersebut, apakah berakhirnya tindak pidana desersi ditentukan pada saat kasusnya dilakukan penyidikan atau pada saat perkaranya disidangkan meskipun pelaku tindak pidana desersi belum kembali.
b. Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa “Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”.
Apabila kita mencermati rumusan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa rumusannya bersifat imperatif, artinya perintah yang tidak bisa dimaknai lain agar pengadilan menyidangkan perkara desersi secara in absensia. Dari rumusan pasal 141 tersebut ada dua hal pokok yang substansial yakni Terdakwanya tidak diketemukan, dan persidangan dilaksanakan secara in absensia.
Apabila kita cermati rumusan kata-kata “Terdakwanya…….” maka dapat dipahami bahwa untuk berkas tersebut Terdakwanya tidak ada ketika perkaranya akan disidangkan, maka persidangan dilaksanakan secara in absensia. Berbeda dengan rumusan Pasal 124 ayat (4), yang menegaskan Tersangkanya yang tidak diketemukan maka penyidikan dilakukan secara in absensia.
Permasalahannya, bagaimana apabila Terdakwa hadir di persidangan apakah pemeriksaan perkara tersebut bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan desersi biasa (bukan in absensia) atau harus dihentikan?.
c. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: “Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.
- Penjelasan Pasal 143
Ketentuan penjelasan tersebut merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian in absensia” adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak
diketemukan lagi dalam jangka waktu enam bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat dari keterangan Komandan atau Kepala Satuannya. Penghitungan tenggang waktu enam bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.
Substansi rumusan pasal 143 tersebut memberikan persyaratan untuk Persidangan desersi secara in absensia, yaitu:
1) Batas waktu berkas perkara adalah enam bulan dihitung tanggal pelimpahan ke Pengadilan.
2) Telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak tiga kali.
3) Dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara in absensia.
Apabila dicermati, persyaratan yang dirumuskan dalam pasal 143 tersebut, sudah bersifat limitative dan imperative, sehingga pengadilan hanya melaksanakan yang diperintahkan oleh Undang-undang. Ternyata dalam prakteknya banyak permasalahan, utamanya dihadapkan pada tuntutan satuan yang menghendaki percepatan penyelesaian agar cepat mendapatkan kepastian hukum dengan pertimbangan bahwa secara nyata prajurit tersebut sudah tidak
ada lagi di kesatuan. Oleh karenanya ada pemikiran untuk menyimpangi ketentuan acara demi untuk percepatan, yakni:
1) Apakah batas waktu enam bulan dan pemanggilan sidang tiga kali secara berturut-turut bersifat imperative atau bersifat tentative.
2) Bagaimana kemungkinan penyelesaian perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara in absensia dengan perkara desersi yang Terdakwanya tidak hadir saja dalam sidang, dikaitkan dengan ketentuan waktu?
3) Bagaimana untuk menentukan akhir dari pelaksanaan waktu desersi, apakah sampai pada saat perkara disidik atau ketika perkara disidangkan.
Dari uraian tersebut dapat dikemukakan inventarisasi permasalahan yang berkenaan dengan persidangan perkara desersi secara in absensia, yakni:
- Mengenai batasan tindak pidana desersi in absensia.
Apakah desersi in absensia sebagai perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara in absensia, atau juga perkara desersi yang Terdakwanya tidak hadir dipersidangan?.
- Perkara desersi yang disidik secara in absensia, akan tetapi Terdakwa hadir di persidangan, dapatkah pemeriksaannya dilanjutkan?
- Penerapan limit waktu enam bulan, dan tenggang waktu pemanggilan tiga kali, dalam penyelesaian perkara desersi in absensia. Apakah dapat disimpangi, untuk alasan percepatan dan kepentingan pembinaan satuan?.
- Tentang akhir waktu penghitungan desersi.
Permasalahan tersebut di atas, ada kesamaan dengan bahan TOR (Terms Of Reference) yang disampaikan oleh Panitia untuk dibahas dalam pelaksanaan pembinaan teknis hakim pada bulan Juli 2010 di Surabaya.
Terms of reference yang disampaikan panitia tersebut, sangat tepat karena hampir disetiap pegadilan militer dalam menyidangkan perkara desersi secara in absensia, kerap menemukan perbedaan pendapat dalam membuat tafsir terhadap ketentuan persidangan perkara desersi secara in absensia.
2. Upaya mengatasi masalah
Untuk kesamaan pendapat, dalam memecahkan perbedaan pendapat selama ini mengenai ketentuan pelaksanaan sidang perkara desersi secara in absensia, dapat dikemukakan pendapat untuk dijadikan pedoman sebagai berikut:
a. Mengenai batasan tentang tindak pidana desersi in absensia:
Pada awal penerapan UU No. 31 Tahun 1997, ada pihak yang berpendapat bahwa untuk dapat disidangkan secara in absensia, adalah tindak pidana desersi yang pelakunya tidak diketemukan lagi, sehingga penyidikan perkara tersebut dilakukan tanpa hadirnya Tersangka. Atas dasar tindakan penyidikan inilah maka persidangannya juga dilakukan secara in absensia karena memang dari sejak awal sudah merupakan perkara in absensia.
Pendapat ini mendasarkan pemahamannya terhadap pasal 124 danpenjelasan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Konsekuensi yuridis dari pendapat ini, apabila ternyata Terdakwa yang disidik secara in absensia, hadir dipersidangan maka pemeriksaan harus ditunda, dan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan secara in absensia tersebut di kembalikan kepada penyidik untuk memeriksa ulang Tersangka secara biasa.
Pendapat ini menegaskan bahwa perkara desersi yang bisa disidangkan secara in absensia hanya perkara desersi yang disidik secara in absensia.
Pendapat lainnya, menegaskan bahwa persidangan perkara desersi secara in absensia dapat juga dilaksanakan terhadap perkara-perkara desersi yang penyidikannya tidak dilakukan secara in absensia, tetapi Terdakwanya setelah itu tidak diketemukan lagi sehingga tidak bisa dihadirkan di persidangan.
Dengan demikian, menurut pendapat kedua ini, bahwa terhadap semua perkara desersi baik yang penyidikannya dilakukan secara in absensia maupun yang penyidikannya dilakukan secara biasa, dapat disidangkan secara in absensia, apabila Terdakwanya tidak bisa dihadirkan di persidangan.
Pendapat ini mendasarkan pemahamannya terhadap ketentuan pasal 141 ayat 10 dan penjelasan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, saya meminta agar saudara memedomani pendapat yang kedua.
b. Persidangan perkara desersi yang disidik secara in absensia, dalam kenyataan Terdakwa hadir di persidangan.
Permasalahan ini, apabila dihadapkan dengan pendapat yang kedua, tidak ada permasalahan, karena pendapat ini meletakkan persoalan pada ketidakhadiran Terdakwa pelaku desersi di persidangan. Sehingga dengan hadirnya Terdakwa di persidangan, maka sidang dapat dilanjutkan karena sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa pada saat penyidikan. Namun demikian, bagi pendapat pertama, persoalan-nya menjadi lain, karena sebelumnya ketika
dilakukan penyidikan, Tersangka belum pernah diperiksa. Oleh karena Terdakwa hadir di persidangan ketika perkaranya akan diperiksa, maka persidangan harus dihentikan, dalam keadaan ini apabila sidang belum dimulai maka kepala pengadilan membuat penetapan untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Kaotmil dengan permintaan penyidik melakukan pemeriksaan Tersangka yang bersangkutan.
Namun apabila sidang sudah dibuka, maka Hakim ketua membuat penetapan pengembalian berkas perkara tersebut kepada Oditur dengan permintaan diteruskan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan kepada Tersangka.
c. Tentang penerapan tenggang waktu selama enam bulan, dan pemanggilan sebanyak tiga kali dalam persidangan desersi secara in absensia.
Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya telah merumuskan secara tegas persyaratan untuk dapatnya tindak pidana desersi disidangkan secara in absensia. Persyaratan tersebut adalah:
- Terdakwanya tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturutturut.
- Sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali berturut-turut secara sah.
Sebagai penjelasan dari syarat yang pertama bahwa tenggang waktu enam bulan tersebut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan. Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran bahwa benar Terdakwa sudah tidak diketemukan lagi, harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan Kesatuannya.
Mengenai syarat formalitas yang dirumuskan dalam pasal 143 tersebut, ada perbedaan pendapat, pertama menyatakan bahwa syarat tersebut dapat diterobos. Aliran progresif ini menekankan bahwa efektifitas dan efisiensi suatu percepatan penyelesaian perkara menjadi pertimbangan utama, bukankah Komandan Kesatuan telah menyatakan Terdakwa sejak pergi meninggalkan kesatuan tidak kembali lagi, dan kenyataannya Terdakwa tidak kembali. Apabila persidangan lebih cepat, akan ada kepastian hukum, dan kesatuan diuntungkan
karena persoalan tersebut tidak menjadi beban lagi. Karenanya tenggang waktu enam bulan tersebut, dipandang sebagai hal yang berlarut-larut dan tidak efektif.
Bukankah ada adagium bahwa “Menunda-nunda keadilan, sama dengan meniadakan keadilan itu sendiri (justice delayed is justice denied)”.
Pendapat kedua, bahwa rumusan pasal 143 dan penjelasannya sudah sangat jelas, rumusan tersebut bersifat limitative dan imperative karenanya kita hanya melaksanakan apa yang dinyatakan dan diperintahkan Undang-undang.
Pendapat ini dilandasi pemikiran, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan juga muaranya pada keadilan, maka hakim dan penegak hokum harus melaksanakan Undang-undang. Penafsiran baru bisa dilakukan dalam rangka Rechts Vinding atau Rechts Schepping, apabila Undang-undangnya tidak jelas atau belum ada hukum yang mengaturnya. Persoalan tenggang waktu enam bulan yang dirumuskan dalam Undang-undang, bukan tidak ada makna
dan tujuannya.
Terhadap perbedaan pendapat tersebut, saya memedomani pendapat yang kedua, oleh karenanya dalam kesempatan ini, perlu saya tekankan bahwa untuk dapat menyidangkan perkara desersi secara in absensia harus ditaati dan dipedomani persyaratan yang digariskan dalam pasal 143 tersebut di atas.
Ketentuan batas waktu enam bulan tersebut, berlaku juga bagi perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara in absensia. Dengan demikian, pemeriksaan perkara desersi secara in absensia yang dilakukan tidak sesuai ketentuan apapun alasan dan pertimbangannya, tidak dibenarkan karena bertentangan dengan persyaratan formal yang dirumuskan dalam Undang-undang.
Permasalahan lain yang berkaitan dengan pemanggilan yang ditentukan harus tiga kali, adalah apakah dimungkinkan melakukan pemeriksaan kepada saksi atau para saksi yang ternyata hadir dalam panggilan pertama atau kedua?.
Pertanyaan ini, sering disampaikan oleh hakim dari beberapa pengadilan militer yang pernah melakukan pemeriksaan saksi pada saat panggilan pertama.
Terhadap persoalan ini, saya ingin memberikan pendapat sekaligus penekanan, bahwa pemeriksaan perkara desersi secara in absensia adalah sama dengan pemeriksaan perkara-perkara lainnya, yang membedakan adalah sidang dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa. Dengan demikian sesuai dengan hukum acara, bahwa pemeriksaan saksi harus didengarkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal keterangan Saksi tersebut.
Dalam hal pemeriksaan perkara desersi secara in absensia, pemeriksaan Saksi dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa, tentunya setelah sidang dinyatakan secara in absensia, dan karenanya pemeriksaan saksi tersebut dibenarkan pelaksanaannya oleh hukum acara. Kapan hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara desersi dilakukan secara in absensia, tentu saja sesudah Oditur melakukan pemanggilan tiga kali secara sah. Oleh karena itu, dalam
sidang pemanggilan yang pertama dan kedua bahwa sidang tersebut belum dinyatakan sebagai pelaksanaan sidang secara in absensia. Dengan demikian, pemeriksaan Saksi tersebut tidak bisa dilaksanakan pada siding pertama dan kedua. Hal yang dapat berakibat fatal apabila Saksi di periksa pada panggilan pertama adalah, jika ternyata pada panggilan yang kedua Terdakwa hadir di persidangan.
Ada contoh kasus yang berkenaan dengan ketentuan pemanggilan tiga kali ini, yaitu kasus desersi seorang Bintara suatu batalyon yang disidangkan pada pengadilan militer Bandung. Dalam panggilan sidang pertama, Terdakwa tidak hadir dan saat itu mendapat penjelasan dari Kasi Pers Batalyon bahwa Terdakwa masih desersi. Setelah lama tertunda pada sidang kedua Oditur tidak melakukan pemanggilan ulang dengan anggapan bahwa keadaan Terdakwa
masih desersi, dan karenanya mohon kepada Majelis perkara desersinya disidangkan secara in absensia. Kemudian majelis menyidangkan perkara tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa. Putusan tersebutdisampaikan oleh Oditur kepada Kesatuan Terdakwa, dan tanpa disangka mendapat penjelasan dari Kesatuan, bahwa Terdakwa sudah lama kembali dan pada saat sidang dilaksanakan Terdakwa saat itu sedang melaksanakan tugas operasi militer, sementara putusan telah berkekuatan Hukum Tetap.
d. Mengenai penghitungan jangka waktu desersi
Terhadap permasalahan ini ada pendapat, yang mengatakan bahwa penentuan waktu batas akhir desersi ketika perkara tersebut dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
Pendapat lainnya adalah, menentukan batas waktu akhir desersi berdasarkan waktu ditandatanganinya surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera) oleh Papera. Sedangkan pendapat ketiga, menyatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Desersi
Cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya. Cara-cara tersebut dapat ditempuh melalui Hukum Pidana Militer, yang akan diselesaikan melalui peradilan militer. Yang kedua yaitu melalui Hukum Disiplin militer yang proses penanganannya diserahkan pada Ankum. Dan yang ketiga yaitu melalui Hukum Administrasi Militer, dengan jalan mengenakan tindakan administrasi seperti schorsing pada setiap prajurit yang melakukan perbuatan tersebut. Dan upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulanginya dapat dilakukan secara preventif, yaitu merupakan upaya pencegahan timbulnya desersi tersebut. Dan dapat pula dilakukan secara Represif, yaitu upaya menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi.
Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu, dikeluarkan Surat Keputusan KASAD Nomor : SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD, sebagai penjabaran dari Skep Pangab Nomor : Skep/711/X/1989 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI.
Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melewati beberapa tahap/tingkatan sebagai berikut :
1. Tingkat penyidikan
2. Tingkat penuntutan
3. Tingkat pemeriksaan di persidangan
4. Tingkat putusan
Tahapan-tahapan tersebut di atas hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di Peradilan Umum, hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara, yang berbeda. Jika dalam peradilan umum yang berhak menjadi penyidik adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:
1. Penyidik adalah :
a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Sedangkan di Peradilan Militer yang mempunyai hak menjadi penyidik adalah “pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI dan atau mereka yang tunduk pada Peradilan Militer” yaitu Polisi Militer sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang tata peradilan militer.
Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Hak penyidik pada
1. Para Ankum Terhadap anak buahnya (Ankum)
2. Polisi militer (POM)
3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer)
Keputusan PANGAB Nomor : Skep/04/P/II/1984/tanggal 4 April 1984 tentang fungsi Penyelenggaraan ke POM di lingkungan ABRI (Skep/711/X/1989).
Dengan demikian Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakkan norma-norma hukum di dalam lingkungan ABRI. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan ABRI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdiannya maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer.
A. Pengertian Desersi dan Macam-Macam Tindak Pidana Desersi
Menurut kamus bahasa Indonesia desersi adalah (perbuatan) lari meninggalkan dinas ketentaraan; pembelotan kepada musuh; perbuatan lari dan memihak kapada musuh.
Pengertian atau definisi dari desersi tersebut dapat disimpulkan dari pasal 87 KUHPM, bahwa desersi adalah tidak hadir dan tidak sah lebih dari 30 hari pada waktu damai dan lebih dari 4 hari pada waktu perang. Ciri utama dari tindak pidana desersi ini adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat dan waktu yang ditentukan baginya dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas.
Dalam perumusan pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam jenis tindak pidana desersi yaitu :
1. Tindak pidana desersi murni diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM.
2. Tindak pidana desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin, diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 dan ke-3 KUHPM.
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Desersi
Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tindak pidana desersi. Adapun tindak pidana desersi ini diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berbunyi :
1. Diancam karena desersi, Militer :
Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, dihindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
Ke-2, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;
Ke-3, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karena tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintah.
2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.
Apabila kita cermati substansi rumusan pasal tersebut, sesuai dengan penempatannya dibawah judul mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, maka dapat dipahami bahwa hakekat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer.
Sikap tersebut dapat saja terealisasikan dalam perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamanya.
Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana ia harus berada, tanpa itu sukar dapat diharapkan dari padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya.
Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer.
Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi.
Apabila kita mencermati makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, secara sepintas perbuatan tersebut, menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali lagi ketempat tugasnya.
Mungkin saja hal ini dapat dilihat dari suatu kenyataan bahwa ia telah bekerja pada suatu perusahaan, tanpa menyatakan pekerjaan tersebut hanya bersifat sementara.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hakikat dari tindak pidana desersi, bukan hanya sekedar perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam tenggang waktu tiga puluh hari. Melainkan harus di maknai bahwa hakikat dari perbuatan desersi tersebut, terkandung maksud tentang sikap dan kehendak pelaku untuk menarik diri dari kewajiban dinasnya dan karenanya harus ditafsirkan bahwa pada diri prajurit tersebut terkandung kehendak atau keinginan bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk tetap berada dalam dinas militer. Hal ini harus dipahami oleh para penegak hukum dilingkungan TNI, khususnya para hakim militer agar dalam memeriksa dan mengadili perkara desersi dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan kesatuan militer.
Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataan, sering terjadi motivasi seorang prajurit melakukan desersi, dikarenakan rasa takut kepada seniornya akibat suatu kesalahan, sehingga ia memilih untuk pergi meninggalkan dinas karena apabila ia ada di kesatuan akan menghadapi tindakan keras dari seniornya. Hal lainnya adalah dikarenakan banyak hutang disana-sini sehingga ia lebih memilih pergi meninggalkan kesatuan ketimbang menyelesaikan masalahnya itu, dan banyak juga motivasi lainnya.
Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana desersi ada 2 macam yaitu:
1. Faktor ekstern meliputi :
a. Perbedaan status sosial yang mencolok
b. Terlibat perselingkuhan/mempunyai wanita idaman lain (WIL)
c. Jenuh dengan peraturan/ingin bebas
d. Trauma perang
e. Mempunyai banyak hutang
f. Silau dengan keadaan ekonomi orang lain
2. Faktor intern meliputi :
a. Kurangnya pembinaan mental (Bintal)
b. Krisis kepemimpinan
c. Pisah keluarga
Untuk mencegah terjadinya perkara tindak pidana di lingkungan TNI, maka setiap satuan hendaknya :
1. Meningkatkan efektifitas pengawasan melekat atau pengawasan internal sebagai salah satu fungsi komando.
2. Melaksanakan program pembinaan personel dan pembinaan mental untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan prajurit terhadap ajaran agama, etika dan moral serta peraturan hukum dan tata tertib.
3. Mengadakan evaluasi faktor penyebab terjadinya perkara, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.
4. Menindak tegas prajurit TNI yang terlibat perkara pidana dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menghindarkan proses penyelesaian yang berlarut-larut.
C. Hambatan Penyelesaian Perkara Desersi Ciri utama tindak pidana desersi ditunjukkan dengan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin seorang militer pada suatu tempat yang ditentukan baginya, dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas.
Diluar organisasi militer, perbuatan ketidakhadiran ini tidak ditentukan sebagai suatu kejahatan, tetapi dalam kehidupan militer ditentukan sebagai kejahatan dan kepada pelakunya apat dijatuhi pidana penjara bahkan sampai pemidana-an yang paling berat yakni penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer. Pemberian sanksi tersebut, sesuai dengan hakikat dan akibat dari tindak pidana desersi, dimana kesatuan yang bersangkutan tidak dapat mendayagunakan tenaga dan pikiran personel tersebut untuk melaksanakan tugas pokok.
Pelaksanaan persidangan tindak pidana desersi sering menemui hambatan dikarenakan pelakunya tidak kembali atau tidak berhasil ditangkap sehingga Terdakwa tidak bisa dihadirkan di persidangan. Akibatnya terjadi tunggakan penyelesaian perkara, dan bagi kesatuan dapat berpengaruh terhadap pembinaan satuan dan pencapaian tugas pokok satuan.
Dalam praktek peradilan, tindak pidana tersebut kerap menimbulkan kesulitan antara lain yang berkenaan dengan penentuan locus dan tempos delicti yang ada kaitannya dengan kompetensi pegadilan misalnya: seorang Kapten X anggota Kodam A mendapat perintah untuk mutasi ke Kodam Jayapura. Yang bersangkutan berdasarkan surat perintah dari Pangdam A, telah melapor kepada atasannya untuk melaksanakan perintah mutasi ke Kodam Jayapura.
Namun dalam kenyataannya, Kapten X tidak segera berangkat ke Kodam Jayapura, baru setelah lewat waktu enam bulan, Kapten X berangkat ke Jayapura dan melapor kepada Komandan Satuan di Kodam Jayapura. Selanjutnya Kapten X oleh Atasannya diserahkan kepada Penyidik Polisi Militer, karena diduga tidak hadir tanpa izin lebih lama dari 30 hari.
Persoalan yang timbul dari posisi kasus tersebut adalah; apakah ia diduga melakukan desersi, dimana locus delicti dan sejak kapan menentukan awal tempos delictinya, atau apakah melakukan tindak pidana insubordinasi (pembangkangan terhadap perintah dinas, karena tidak melaksanakan perintah mutasi/pindah kesatuan ke Kodam Jayapura). Dilihat dari sudut tugas dan kewajiban Kapten X untuk berada dikesatuan guna melaksanakan tugas kewajibannya sebagai Perwira di Kodam Jayapura, maka kepadanya dapat diterapkan tindak pidana desersi. Tetapi apabila penekanannya terhadap pelaksanaan surat perintah yang dikeluarkan Kodam A untuk melaksanakan mutasi, ternyata ia tidak melaksanakannya atau melaksanakan dengan semaunya, maka kepadanya dapat diterapkan pembangkangan atau insubordinasi. Demikian pula dari aspek tempos, sejak kapan Kapten X melakukan ketidakhadiran, apakah setelah yang bersangkutan melapor kepada atasannya di Kodam A. Untuk penerapan tindak pidana desersi, penentuan tempos ini perlu diperhatikan karena untuk menentukan lama ketidakhadiran seorang prajurit di kesatuan. Demikian pula, harus ditentukan dimana kesatuan yang ia tinggalkan, karena yang bersangkutan belum melapor ke tempat satuan baru.
Kesulitan dalam praktek untuk menghadirkan para pelaku tindak pidana desersi ke muka sidang, telah disadari oleh pembuat Undang-undang, karenanya pembuat Undang-undang telah merumuskan secara limitatif dalam sebuah pasal untuk menyidangkan perkara desersi secara in absensia.
1. Persidangan perkara desersi secara in absensia
Ketentuan ini dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dirumuskan dalam beberapa pasal, yakni:
a. Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: “Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara”.
Substansi dari rumusan pasal 124 ayat (4) tersebut:
1) Bahwa pemeriksaan Tersangka bukan merupakan syarat formal
2) Pemberkasan perkara desersi yang dilaporkan oleh Satuan kepada Penyidik dapat dilakukan meskipun Tersangka tidak ada.
Dengan demikian dari substansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana desersi ini dilakukan tanpa hadirnya Tersangka, karenanya dinamakan penyidikan perkara desersi in absensia.
Kemudian terhadap berkas hasil penyidikan ini akan disidangkan secara in absensia. Ketentuan formalitas tersebut terdapat permasalahan, yakni mengenai penentuan tempos delicti, yaitu sampai kapan waktu desersi tersebut, apakah berakhirnya tindak pidana desersi ditentukan pada saat kasusnya dilakukan penyidikan atau pada saat perkaranya disidangkan meskipun pelaku tindak pidana desersi belum kembali.
b. Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa “Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”.
Apabila kita mencermati rumusan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa rumusannya bersifat imperatif, artinya perintah yang tidak bisa dimaknai lain agar pengadilan menyidangkan perkara desersi secara in absensia. Dari rumusan pasal 141 tersebut ada dua hal pokok yang substansial yakni Terdakwanya tidak diketemukan, dan persidangan dilaksanakan secara in absensia.
Apabila kita cermati rumusan kata-kata “Terdakwanya…….” maka dapat dipahami bahwa untuk berkas tersebut Terdakwanya tidak ada ketika perkaranya akan disidangkan, maka persidangan dilaksanakan secara in absensia. Berbeda dengan rumusan Pasal 124 ayat (4), yang menegaskan Tersangkanya yang tidak diketemukan maka penyidikan dilakukan secara in absensia.
Permasalahannya, bagaimana apabila Terdakwa hadir di persidangan apakah pemeriksaan perkara tersebut bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan desersi biasa (bukan in absensia) atau harus dihentikan?.
c. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: “Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.
- Penjelasan Pasal 143
Ketentuan penjelasan tersebut merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian in absensia” adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak
diketemukan lagi dalam jangka waktu enam bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat dari keterangan Komandan atau Kepala Satuannya. Penghitungan tenggang waktu enam bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.
Substansi rumusan pasal 143 tersebut memberikan persyaratan untuk Persidangan desersi secara in absensia, yaitu:
1) Batas waktu berkas perkara adalah enam bulan dihitung tanggal pelimpahan ke Pengadilan.
2) Telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak tiga kali.
3) Dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara in absensia.
Apabila dicermati, persyaratan yang dirumuskan dalam pasal 143 tersebut, sudah bersifat limitative dan imperative, sehingga pengadilan hanya melaksanakan yang diperintahkan oleh Undang-undang. Ternyata dalam prakteknya banyak permasalahan, utamanya dihadapkan pada tuntutan satuan yang menghendaki percepatan penyelesaian agar cepat mendapatkan kepastian hukum dengan pertimbangan bahwa secara nyata prajurit tersebut sudah tidak
ada lagi di kesatuan. Oleh karenanya ada pemikiran untuk menyimpangi ketentuan acara demi untuk percepatan, yakni:
1) Apakah batas waktu enam bulan dan pemanggilan sidang tiga kali secara berturut-turut bersifat imperative atau bersifat tentative.
2) Bagaimana kemungkinan penyelesaian perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara in absensia dengan perkara desersi yang Terdakwanya tidak hadir saja dalam sidang, dikaitkan dengan ketentuan waktu?
3) Bagaimana untuk menentukan akhir dari pelaksanaan waktu desersi, apakah sampai pada saat perkara disidik atau ketika perkara disidangkan.
Dari uraian tersebut dapat dikemukakan inventarisasi permasalahan yang berkenaan dengan persidangan perkara desersi secara in absensia, yakni:
- Mengenai batasan tindak pidana desersi in absensia.
Apakah desersi in absensia sebagai perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara in absensia, atau juga perkara desersi yang Terdakwanya tidak hadir dipersidangan?.
- Perkara desersi yang disidik secara in absensia, akan tetapi Terdakwa hadir di persidangan, dapatkah pemeriksaannya dilanjutkan?
- Penerapan limit waktu enam bulan, dan tenggang waktu pemanggilan tiga kali, dalam penyelesaian perkara desersi in absensia. Apakah dapat disimpangi, untuk alasan percepatan dan kepentingan pembinaan satuan?.
- Tentang akhir waktu penghitungan desersi.
Permasalahan tersebut di atas, ada kesamaan dengan bahan TOR (Terms Of Reference) yang disampaikan oleh Panitia untuk dibahas dalam pelaksanaan pembinaan teknis hakim pada bulan Juli 2010 di Surabaya.
Terms of reference yang disampaikan panitia tersebut, sangat tepat karena hampir disetiap pegadilan militer dalam menyidangkan perkara desersi secara in absensia, kerap menemukan perbedaan pendapat dalam membuat tafsir terhadap ketentuan persidangan perkara desersi secara in absensia.
2. Upaya mengatasi masalah
Untuk kesamaan pendapat, dalam memecahkan perbedaan pendapat selama ini mengenai ketentuan pelaksanaan sidang perkara desersi secara in absensia, dapat dikemukakan pendapat untuk dijadikan pedoman sebagai berikut:
a. Mengenai batasan tentang tindak pidana desersi in absensia:
Pada awal penerapan UU No. 31 Tahun 1997, ada pihak yang berpendapat bahwa untuk dapat disidangkan secara in absensia, adalah tindak pidana desersi yang pelakunya tidak diketemukan lagi, sehingga penyidikan perkara tersebut dilakukan tanpa hadirnya Tersangka. Atas dasar tindakan penyidikan inilah maka persidangannya juga dilakukan secara in absensia karena memang dari sejak awal sudah merupakan perkara in absensia.
Pendapat ini mendasarkan pemahamannya terhadap pasal 124 danpenjelasan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Konsekuensi yuridis dari pendapat ini, apabila ternyata Terdakwa yang disidik secara in absensia, hadir dipersidangan maka pemeriksaan harus ditunda, dan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan secara in absensia tersebut di kembalikan kepada penyidik untuk memeriksa ulang Tersangka secara biasa.
Pendapat ini menegaskan bahwa perkara desersi yang bisa disidangkan secara in absensia hanya perkara desersi yang disidik secara in absensia.
Pendapat lainnya, menegaskan bahwa persidangan perkara desersi secara in absensia dapat juga dilaksanakan terhadap perkara-perkara desersi yang penyidikannya tidak dilakukan secara in absensia, tetapi Terdakwanya setelah itu tidak diketemukan lagi sehingga tidak bisa dihadirkan di persidangan.
Dengan demikian, menurut pendapat kedua ini, bahwa terhadap semua perkara desersi baik yang penyidikannya dilakukan secara in absensia maupun yang penyidikannya dilakukan secara biasa, dapat disidangkan secara in absensia, apabila Terdakwanya tidak bisa dihadirkan di persidangan.
Pendapat ini mendasarkan pemahamannya terhadap ketentuan pasal 141 ayat 10 dan penjelasan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, saya meminta agar saudara memedomani pendapat yang kedua.
b. Persidangan perkara desersi yang disidik secara in absensia, dalam kenyataan Terdakwa hadir di persidangan.
Permasalahan ini, apabila dihadapkan dengan pendapat yang kedua, tidak ada permasalahan, karena pendapat ini meletakkan persoalan pada ketidakhadiran Terdakwa pelaku desersi di persidangan. Sehingga dengan hadirnya Terdakwa di persidangan, maka sidang dapat dilanjutkan karena sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa pada saat penyidikan. Namun demikian, bagi pendapat pertama, persoalan-nya menjadi lain, karena sebelumnya ketika
dilakukan penyidikan, Tersangka belum pernah diperiksa. Oleh karena Terdakwa hadir di persidangan ketika perkaranya akan diperiksa, maka persidangan harus dihentikan, dalam keadaan ini apabila sidang belum dimulai maka kepala pengadilan membuat penetapan untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Kaotmil dengan permintaan penyidik melakukan pemeriksaan Tersangka yang bersangkutan.
Namun apabila sidang sudah dibuka, maka Hakim ketua membuat penetapan pengembalian berkas perkara tersebut kepada Oditur dengan permintaan diteruskan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan kepada Tersangka.
c. Tentang penerapan tenggang waktu selama enam bulan, dan pemanggilan sebanyak tiga kali dalam persidangan desersi secara in absensia.
Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya telah merumuskan secara tegas persyaratan untuk dapatnya tindak pidana desersi disidangkan secara in absensia. Persyaratan tersebut adalah:
- Terdakwanya tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturutturut.
- Sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali berturut-turut secara sah.
Sebagai penjelasan dari syarat yang pertama bahwa tenggang waktu enam bulan tersebut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan. Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran bahwa benar Terdakwa sudah tidak diketemukan lagi, harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan Kesatuannya.
Mengenai syarat formalitas yang dirumuskan dalam pasal 143 tersebut, ada perbedaan pendapat, pertama menyatakan bahwa syarat tersebut dapat diterobos. Aliran progresif ini menekankan bahwa efektifitas dan efisiensi suatu percepatan penyelesaian perkara menjadi pertimbangan utama, bukankah Komandan Kesatuan telah menyatakan Terdakwa sejak pergi meninggalkan kesatuan tidak kembali lagi, dan kenyataannya Terdakwa tidak kembali. Apabila persidangan lebih cepat, akan ada kepastian hukum, dan kesatuan diuntungkan
karena persoalan tersebut tidak menjadi beban lagi. Karenanya tenggang waktu enam bulan tersebut, dipandang sebagai hal yang berlarut-larut dan tidak efektif.
Bukankah ada adagium bahwa “Menunda-nunda keadilan, sama dengan meniadakan keadilan itu sendiri (justice delayed is justice denied)”.
Pendapat kedua, bahwa rumusan pasal 143 dan penjelasannya sudah sangat jelas, rumusan tersebut bersifat limitative dan imperative karenanya kita hanya melaksanakan apa yang dinyatakan dan diperintahkan Undang-undang.
Pendapat ini dilandasi pemikiran, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan juga muaranya pada keadilan, maka hakim dan penegak hokum harus melaksanakan Undang-undang. Penafsiran baru bisa dilakukan dalam rangka Rechts Vinding atau Rechts Schepping, apabila Undang-undangnya tidak jelas atau belum ada hukum yang mengaturnya. Persoalan tenggang waktu enam bulan yang dirumuskan dalam Undang-undang, bukan tidak ada makna
dan tujuannya.
Terhadap perbedaan pendapat tersebut, saya memedomani pendapat yang kedua, oleh karenanya dalam kesempatan ini, perlu saya tekankan bahwa untuk dapat menyidangkan perkara desersi secara in absensia harus ditaati dan dipedomani persyaratan yang digariskan dalam pasal 143 tersebut di atas.
Ketentuan batas waktu enam bulan tersebut, berlaku juga bagi perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara in absensia. Dengan demikian, pemeriksaan perkara desersi secara in absensia yang dilakukan tidak sesuai ketentuan apapun alasan dan pertimbangannya, tidak dibenarkan karena bertentangan dengan persyaratan formal yang dirumuskan dalam Undang-undang.
Permasalahan lain yang berkaitan dengan pemanggilan yang ditentukan harus tiga kali, adalah apakah dimungkinkan melakukan pemeriksaan kepada saksi atau para saksi yang ternyata hadir dalam panggilan pertama atau kedua?.
Pertanyaan ini, sering disampaikan oleh hakim dari beberapa pengadilan militer yang pernah melakukan pemeriksaan saksi pada saat panggilan pertama.
Terhadap persoalan ini, saya ingin memberikan pendapat sekaligus penekanan, bahwa pemeriksaan perkara desersi secara in absensia adalah sama dengan pemeriksaan perkara-perkara lainnya, yang membedakan adalah sidang dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa. Dengan demikian sesuai dengan hukum acara, bahwa pemeriksaan saksi harus didengarkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal keterangan Saksi tersebut.
Dalam hal pemeriksaan perkara desersi secara in absensia, pemeriksaan Saksi dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa, tentunya setelah sidang dinyatakan secara in absensia, dan karenanya pemeriksaan saksi tersebut dibenarkan pelaksanaannya oleh hukum acara. Kapan hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara desersi dilakukan secara in absensia, tentu saja sesudah Oditur melakukan pemanggilan tiga kali secara sah. Oleh karena itu, dalam
sidang pemanggilan yang pertama dan kedua bahwa sidang tersebut belum dinyatakan sebagai pelaksanaan sidang secara in absensia. Dengan demikian, pemeriksaan Saksi tersebut tidak bisa dilaksanakan pada siding pertama dan kedua. Hal yang dapat berakibat fatal apabila Saksi di periksa pada panggilan pertama adalah, jika ternyata pada panggilan yang kedua Terdakwa hadir di persidangan.
Ada contoh kasus yang berkenaan dengan ketentuan pemanggilan tiga kali ini, yaitu kasus desersi seorang Bintara suatu batalyon yang disidangkan pada pengadilan militer Bandung. Dalam panggilan sidang pertama, Terdakwa tidak hadir dan saat itu mendapat penjelasan dari Kasi Pers Batalyon bahwa Terdakwa masih desersi. Setelah lama tertunda pada sidang kedua Oditur tidak melakukan pemanggilan ulang dengan anggapan bahwa keadaan Terdakwa
masih desersi, dan karenanya mohon kepada Majelis perkara desersinya disidangkan secara in absensia. Kemudian majelis menyidangkan perkara tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa. Putusan tersebutdisampaikan oleh Oditur kepada Kesatuan Terdakwa, dan tanpa disangka mendapat penjelasan dari Kesatuan, bahwa Terdakwa sudah lama kembali dan pada saat sidang dilaksanakan Terdakwa saat itu sedang melaksanakan tugas operasi militer, sementara putusan telah berkekuatan Hukum Tetap.
d. Mengenai penghitungan jangka waktu desersi
Terhadap permasalahan ini ada pendapat, yang mengatakan bahwa penentuan waktu batas akhir desersi ketika perkara tersebut dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
Pendapat lainnya adalah, menentukan batas waktu akhir desersi berdasarkan waktu ditandatanganinya surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera) oleh Papera. Sedangkan pendapat ketiga, menyatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Desersi
Cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya. Cara-cara tersebut dapat ditempuh melalui Hukum Pidana Militer, yang akan diselesaikan melalui peradilan militer. Yang kedua yaitu melalui Hukum Disiplin militer yang proses penanganannya diserahkan pada Ankum. Dan yang ketiga yaitu melalui Hukum Administrasi Militer, dengan jalan mengenakan tindakan administrasi seperti schorsing pada setiap prajurit yang melakukan perbuatan tersebut. Dan upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulanginya dapat dilakukan secara preventif, yaitu merupakan upaya pencegahan timbulnya desersi tersebut. Dan dapat pula dilakukan secara Represif, yaitu upaya menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi.
Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu, dikeluarkan Surat Keputusan KASAD Nomor : SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD, sebagai penjabaran dari Skep Pangab Nomor : Skep/711/X/1989 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI.
Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melewati beberapa tahap/tingkatan sebagai berikut :
1. Tingkat penyidikan
2. Tingkat penuntutan
3. Tingkat pemeriksaan di persidangan
4. Tingkat putusan
Tahapan-tahapan tersebut di atas hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di Peradilan Umum, hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara, yang berbeda. Jika dalam peradilan umum yang berhak menjadi penyidik adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:
1. Penyidik adalah :
a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Sedangkan di Peradilan Militer yang mempunyai hak menjadi penyidik adalah “pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI dan atau mereka yang tunduk pada Peradilan Militer” yaitu Polisi Militer sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang tata peradilan militer.
Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Hak penyidik pada
1. Para Ankum Terhadap anak buahnya (Ankum)
2. Polisi militer (POM)
3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer)
Keputusan PANGAB Nomor : Skep/04/P/II/1984/tanggal 4 April 1984 tentang fungsi Penyelenggaraan ke POM di lingkungan ABRI (Skep/711/X/1989).
Dengan demikian Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakkan norma-norma hukum di dalam lingkungan ABRI. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan ABRI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdiannya maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer.
Minggu, 04 Desember 2011
hukum pidana
di dalam hukump pidana ada istilah delik, sebenarnya delik itu mempunyai arti yang sama yaitu pidana.
untuk itu dalam suatu perbuatan dapat dikenai suatu pidana harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perundang-undangan
Rabu, 02 November 2011
Pembaruan Hukum
Pembaruan Hukum:
I. BAB1
PENDAHULUAN
LATAR BLAKANG
Bangsa Indonesia disaat memproklamasikan kemerdekaannya belum mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan yang lengkap. Baru pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan diundangkan UUD 1945 yang memuat aturan-aturan pokok. Untuk mengisi kekosongan hukum, maka Aturan Peralihann UUD 1945 menetapkan berlakunya aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 maka Hukum Pidana (WvS) diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun mempunyai dasar hukum untuk diberlakukan WvS di Indonesia (yaitu aturan peralihan pasal II) namun demikian jelas ini suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi bangsa kita, bagaimanapun hukum yang dibuat oleh Belanda yang notabene adalah bangsa asing, tidak akan bisa mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia secara umum. Usaha untuk mengganti hukum warisan kolonial Belanda bukannya tidak pernah dilakukan. Usaha itu telah dirintis dan terus dilakukan, salahsatunya yang sampai sekarang belum selesai adalah pembaharuan KUHP.
Adapun WvS (selanjutnya disebut KUHP / Kitab Undang-undangHukum Pidana) kemudian diberlakukan dengan UU nomor 1 tahun 1946 yang ditetapkan pada tanggal 26 Pebruari 1946. Adapun bunyi dari pada UU ini adalah: “menimbang, bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan UU hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana yang disesuaikan dengan keadaan sekarang”. Dengan demikian maka UU ini merupakan peraturan peralihan, yang memuat hukum transitoir, yang tampak dalam pasal I, yang menetapkan, “bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hokum pidana yang ada pada tanggal 8 maret 1945”. Pada tanggal tersebut, yang berlaku ialah peraturan hukum pidana Belanda, akan tetapi dalam pasal II Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa, semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh panglima bala tentara Hindia Belanda dicabut, antara lain peraturan hukum pidana yang memuat ancaman pidana, dalam larangan menimbun barang. Sehubungan dengan itu ada juga produk perundang-undangan yang memperbaharui kemudian dimasukkan kedalam pasal-pasal KUHP. Misalnya antara lain, UU No. 20 tahun 1946 yang menambah jenis pidana pokok dengan satu pidana baru yaitu mengenai tentang Pidana Tutupan, UU No. 73 tahun 1958 yang mengadakan beberapa perubahan dalam Bab I buku II KUHP, UU No. 4 tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan. Berdasarkan beberapa UU tersebut kemudian pasal-pasal yang ada didalam KUHP ditambah dan dilengkapi. . Disamping peraturan perundangan tersebut diatas, juga yang merupakan delik khusus adalah pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama setelah peristiwa Timor Timur, permasalahan pelanggaran HAM banyak dibahas oleh para ahli. Selanjutnya dengan mengacu kepada UU nomor 39 tahun 1999 dan UU nomor 26 tahun 2000 (Pengadilan HAM), maka dikenal dua bentuk pelanggaran HAM, yaitu palanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pengertian Pelanggaran HAM terdapat dalam Pasal 1 butir 6 dan pengertian Pelanggaran HAM Berat terdapat dalam penjelasan UU No. 39 tahun 1999 yaitu dalam Pasal 104 ayat 1. Pasal 1 butir 6 menyatakan :Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hokum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
II. Perumusan Masalah dan Pembahasan
Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan, maka
permasalahan yang dirumuskan untuk penyususunan thesis ini adalah :
1. Perkembangan Tanggung Jawab Komando Terhadap pelanggaran
HAM yang berat Dan Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional?
2. Penerapan Tanggung Jawab Komando dalam Kasus-kasus
Pelanggaran Berat HAM di Indonesia?
Pembaharuan Hukum Acara Pidana (HAP) merupakan suatu hal yang harus dilakukan bila pemerintah memilki kemauaan untuk memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Hukum acara pidana dalam KUHAP yang menjadi acuan dasar hukum acara pidana sktoral dilupakan padahal, UU Sektoral hanya memberikan penambahan aturan khusus, sedangkan secara umum tetap mempergunakan KUHAP, mudahnya bila tidak terdapat ketentuan dalam UU Sektoral tersebut maka KUHAP yang menjadi acuan.
Pembaharuan KUHAP sebenarnya telah menjadi kebutuhan, tidak hanya karena UU No 8 Tahun 1981 yang familiar KUHAP saat ini banyak menimbulkan permasalahan seperti pelanggaran HAM orang yang berhadapan dengan hukum pidana, penyiksaan untuk mendapatkan pengakuaan atau informasi, tidak jelasnya sistem peradilan pidana di Indonesia, dan jual beli kewenangan (upaya paksa oleh penegak hukum). Permasalahan tersebut terjadi karena lemahnya kontrol internal dalam sistem peradilan pidana itu sendiri, pra peradilan yang diharapkan menjadi kontrol masyarakat terhadap kekuasaan negara yang begitu besar ternyata hanya menjadi kontrol administrative saja dan bersifat amat sangat pasif. Kontrol hakim / ketua pengadilan sebagai bentuk aplikatif kontrol yudikatif terhadap eksekutif pada sistem peradilan pidana tidak mendapatkan kewenangan yang terlalu besar . Lembaga kontrol pengawas eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial hanya menjadi hiasan semata, karena lemahnya kewenangan yang diberikan kepada mereka.
Upaya pembaharuan hukum acara pidana yang dilakukan oleh Tim Pembaharuan Hukum Acara Pidana dengan mempertimbangkan adanya perubahan sosial, teknologi, transportasi dll serta Konsekuensi Indonesia telah mengesahkan (ratifikasi) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang Kejam, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Semangat pembaharuan KUHAP terus mendapatkan hambatan dari berbagai pihak khususnya dari aparatur penegak hukum itu sendiri
Atas dasar itu penting bagi pemerintah untuk Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik, khususnya untuk penahanan sebelum pengadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
I. Perlindungan Praduga Bersalah
Semua negara di dunia, yang mengakui sebagai negara hukum menerapkan asas praduga tak bersalah. Konstitusional Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, Pasal 11 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya sesuai dengan hukum , dalam pengadilan yang terbuka dimana ia memperoleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk melakukan pembelaanya”
Penahanan sebelum adanya putusan hukum yang final, adalah bentuk penginkaran atas hak asasi manusia dan asas Praduga tidak bersalah. Pembatasan atas hak tersebut selain harus secara jelas dinyatakan oleh Undang-Undang. UU No 8 Tahun 1981 (KUHAP) telah mengatur penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulang tindak pidana. KUHAP memberikan wewenang penuh kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk menentukan apakah tersangka/terdaka ditahan atau tidak dengan pertimbangan subyektif karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, penentuan subyektif tersebut haruslah melihat fakta-fakta yang ada, sehingga menjadi penting penentuan tersangka dapat ditahan atau tidak haruslah diambil oleh pihak yang menjalankan fungsi pengadilan dalam hal ini hakim bukan penyidik atau penuntut umum.
Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik berjanji untuk menghormati dan menjamin aturan dalam kovenan baik dalam aturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan yang diambil
Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Konvensi Hak sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005 secara tegas menyatakan “Siapapun yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan kekuasaan pengadilan” ayat (4) menyatakan “Siapapun yang dirampas kemerdekaanya dengan cara penangkapan, mempunyai hak untuk disidangkan di depan pengadilan, agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya dan memerintahkan pembebasan apabila penahanan tersebut tidak sah menurut hukum”
Ketentuan hukum acara pidana yang saat ini diberlakukan di Indonesia melalui UU No 8 Tahun 1981 tidak mengakomodir ketentuan tersebut, Penyidik untuk dan atas kepentingannya dapat melakukan penahanan terhadap orang yang diduga dengan bukti permulaan yang cukup selama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari . Sedangkan Penuntut umum dapat menahan tersangka selama 20 hari. Sehingga Hakim sebagai pemegang kewenangan yudikatif baru mengetahui kondisi tersangka yang ditahan ketika pembacaan dakwaan.
Bila ketentuan tersebut tetap dilanggengkan oleh Pembuat Undang-Undang yang melakukan pembaharuan hukum acara pidana, maka Negara Indonesia dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui regulasi yang dikeluarkan.
3. Perkembangan Tanggung Jawab Komando Terhadap pelanggaran
HAM yang berat Dan Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional.
Di bawah ini dijelaskan beberapa praktik penerapan tanggung jawab komando yang terjadi pada masa awal perkembangan doktrin ini. Beberapa contoh kasus yang terjadi pada masa awal perkembangan doktrin ini, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasisituasi yang memungkinkan seorang komandan atau atasan dimintai pertanggungjawaban karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bawahannya. Dari ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab komando serta proses hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus tersebut, akan dikemukakan elemen-elemen pokok yang menjadi dasar penentuan kesalahan seorang komandan atau atasan atas dasar doktrin tanggung jawab komando atau tanggung jawab atasan. Mulanya, Raja Charles Vll dari Perancis di Orleans pada tahun 1493 mengeluarkan perintah yang tegas berkaitan dengan doktrin tanggung jawab komando. Perintah tersebut menyatakan: ”Raja memerintahkan bahwa setiap kapten atau letnan bertanggung jawab atas
penyimpangan, tindakan buruk dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kompinya, dan setelah ia menerima suatu pengaduan mengenai adanya kesalahan atau penyimpangan tersebut, ia membawa pelakunya ke pengadilan sehingga pelakunya dihukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Jika ia tidak melakukan hal itu atau menutupi kesalahan atau tidak mengambil tindakan, atau jika, karena kelalainnya atau kesengajaannya pelaku kejahatan melarikan diri sehingga terhindar dari hukuman, kapten tersebut harus dianggap bertanggung jawab atas kejahatan tersebut seolah-olah ia telah melakukan sendiri kejahatan itu dan harus dihukum sama seperti yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan”. Beberapa aspek penting mengenai doktrin tanggung jawab komando yang terdapat dalam perintah raja Charles tersebut adalah: pertama, komandan bertanggung jawab untuk mengendalikan perilaku termasuk cara bertindak yang dilaksanakan oleh bawahannya agar tidakmenyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku; kedua, komandan berkewajiban untuk memproses setiap bawahannya yang terlibat sebagai pelaku kejahatan secara hukum; ketiga, jika komandan karena kelalaian atau kesengajaan membiarkan kejahatan terjadi dan tidak melakukan 56 kedua hal tersebut di atas, maka ia bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh prajurit bawahannya. 75 Selanjutnya, perkembangan doktrin tanggung jawab komando ini, diberlakukan oleh penguasa Austria (the archduke of austria) yang pada tahun 1474 ia mengadili Peter Von Hagenbach, yang telah memimpin rangkaian kejahatan selama ia berkuasa untuk kepentingan Charles dari Burgundy di wilayah Upper Rhine yang baru ditaklukkan. Ia dipersalahkan karena melakukan kejahatan perkosaan, pembunuhan, melanggar sumpah dan kejahatan terhadap Tuhan dan manusia (the law of god and man).76 Dalam pembelaannya di depan pengadilan, Peter menyatakan tindakan tersebut dilakukan atas dasar perintah atasan. Namun pengadilan menolak pembelaan atas dasar perintah atasan tersebut dan dalam putusannya menyatakan Peter bersalah melakukan kejahatan yang semestinya ia berkewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Putusan dalam kasus Peter ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa: ”negara dan pejabat yang berkuasa bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah kekuasaannya, jika mereka mengetahui kejahatan tersebut dan tidak melakukan pencegahan padahal mereka dapat dan harus melakukan hal itu”.
Penerapan Tanggung Jawab Komando dalam Kasus-kasus
Pelanggaran Berat HAM di Indonesia.
1. Pengaturan Tanggung Jawab Komando dalam Hukum Positif Hukum hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 mengatur pertanggungjawaban komandan militer sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 42. Di dalam system hukum pidana Indonesia juga dikenal apa yang disebut sebagai pertanggungjawaban pidana. Mengenai istilah ini di dalam bahasa Belanda terdapat tiga kata yang sinonim, yaitu aanspraakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar. Orangnya yang aanspraakelijk atau verantwoordelijk, sedangkan toerekenbaar bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang, biasanya pengarang lain memakai istilah toerekenbaar132. Dalam hal pertanggungjawaban pidana dikenal beberapa pembatasan, yang tidak semua orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP yang mengatur tentang pengecualian pelaku dari 132 Hamzah, S, 1991. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 108 mengutip Pompe 90 pertanggungjawaban pidana. Namun lain halnya dengan pertanggungjawaban di lingkup militer, seorang komandan tidak dapat bebas dari pertanggungjawaban pidana, apabila ia mengetahui bahwa anak buanya telah atau akan melakukan kejahatan yang berhubungan dengan tugas mereka dan sepanjang perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan jika ia tidak mencegah/bertindak dan hanya membiarkan/tidak melakukan sesuatu (omission) maka komandan tersebut tetap dipertanggungjawabkan, karena adanya hubungan khusus, antara komandan (superior) dan bawahan (inferior). Berdasarkan precedents/case law hubungan atasan dan bawahan dapat didasari atas dasar de jure dan de facto. De jure ialah pengangkatan seseorang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hierarki seorang atasan dengan bawahan beserta tugas masing-masing, de facto merupakan hubungan atasan bawahan dalam kenyataannya di lapangan antara lain bagaimana pandangan unit kerja terhadap atasan. Dalam kasus yang diadili oleh pengadilan pidana internasional (ICTR dan ICTY) para terdakwa yang didakwa sebagai seorang atasan oleh karena secara de facto dan de jure adalah kasus akeyashu, yang didakwa karena mempunyai otoritas de Jure dan de facto baik terhadap golongan sipil, maupun polisi dan tentara. Mengenai pertanggungjawaban di lingkup militer sebenarnya bermula dari yurisprudensi yang terkenal, yaitu berkenaan dengan kasuskasus setelah Perang Dunia II terhadap para penjahat perang NAZI Jerman dan Fasis Jepang, yang dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindakan semasa peperangan melalui suatu pengadilan yang dikenal dengan nama “The Nuremberg Trial” dan “The Tokyo Trial” (1948) . Pengadilan yang mengadili penjahat perang Jerman dan Jepang ini memperoleh pengakuan secara resmi dari Majelis Umum PBB melalui resolusinya tanggal 11 Desember 1948. Dengan pengakuan tersebut, maka validitas peradilan Nuremberg dan penerapannya pada kemudian hari, tidak akan dipersoalkan lagi. Bahkan pada masa yang akan datang, yurisdiksi peradilan atas pelaku kejahatan perang diperluas mencakup juga kejahatan terhadap kemanusiaan, dan perdamaian, yang dilakukan dalam kaitan peperangan. Kasus-kasus yang diputus oleh pengadilan militer Internasional (IMT) tersebut antara lain kasus terhadap penjahat perang jepang Jenderal Tomoyuki Yamashita, yang dijatuhi hukuman mati karena terbukti bahwa ia sebagai seorang komandan tertinggi/gubernur militer Jepang di Philipina telah gagal mengawasi bawahannya yang melakukan kejahatan-kejahatan perang dan kekejaman lainnya yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum internasional. Meskipun Yamashita dalam pembelaannya mengatakan bahwa ia tidak mengetahui perbuata pasukannya karena ia kehilangan komunikasi karena jaraknya ratusan mil dari tempatnya, namun Yamashita tetap dipersalahkan sebagai atasan dan bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya yang melakukan kejahatan perang. Kasus jenderal Tomoyuki Yamashita merupakan contoh dalam pertanggungjawabab secara strict liability. Charter International Military Tribunal Nuremberg Trial ini penting artinya karena memuat Prinsip baru yang diterapkan untuk Mahkamah Nuremberg dan Mahkamah Tokyo, antara lain tentang pertanggungjawaban pribadi dan asas retroaktif. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam Statuta ICTY, ICTR, serta pengadilan di Indonesia yaitu dalam UU tentang Pengadilan HAM. Mahkamah Nuremberg juga mengemukakan bahwa prinsip pertanggungjawaban individu dan penghukuman bagi kejahatan-kejahatan internasional, merupakan dasar utama dari hukum pidana internasional. Prinsip ini merupakan warisan abadi yang disumbangkan oleh Piagam dan Putusan Nuremberg (Nuremberg Charter and Judgment) yang meletakkan konsep bagi larangan kejahatan-kejahatan berdasarkan hukum internasional dengan menjamin bahwa individu-individu yang melakukan kejahatan perang akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Karnasudirdja, peradilan Nuremberg dan Tokyo telah menciptakan konsep-konsep hokum internasional baru yang penting dan kemudian diakui oleh PBB dan 93 diadopsi oleh hukum internasional serta dilaksanakan oleh Pengadilan Pidana Internasional lainnya . Lebih lanjut lagi tentang pertanggungjawaban individu ini, Pasal 8 dari Piagam Mahkamah Nuremberg mengatur bahwa perintah dari pemerintah atau atasannya tidak akan membebaskan seseorang dari tanggungjawab pidana, tetapi mungkin dapat dipertimbangkan dalam meringankan hukuman, jika mahkamah menentukan bahwa keadilan amat disyaratkan. Dengan demikian ini berarti bahwa perintah jabatan atau atasan tidak dapat dijadikan alasan penghapus hukuman. Mahkamah Nuremberg juga memutuskan bahwa tiap individu mempunyai kewajiban internasional yang melebihi kepatuhan atas kewajiban-kewajiban nasional yang dipatuhi oleh individu negara. Ini merupakan pemikiran revolusioner yang membatasi kedaulatan mutlak tiap negara, bukan oleh hukum yang ditujukan kepada negara, tetapi oleh hukum yang ditujukan kepada individu. Prinsip tanggungjawab individu tersebut didasarkan pada ketentuan supremasi hukum yang ditetapkan berdasarkan ilham yang ada dalam the Common Law. Dalam ketentuan hukum tersebut dikemukakan bahwa menteri-menteri atau pembantu Raja akan bertanggungjawab secara hukum atas tindakan yang dilakukannya, dan ia tidak dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan alasan bahwa ia bertindak untuk patuh kepada perintah Raja. Mahkamah Nuremberg selanjutnya menyimpulkan Mengenai pertanggungjawaban di lingkup militer sebenarnya bermula dari yurisprudensi yang terkenal, yaitu berkenaan dengan kasus kasus setelah Perang Dunia II terhadap para penjahat perang NAZI Jerman dan Fasis Jepang, yang dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindakan semasa peperangan melalui suatu pengadilan yang dikenal dengan nama “The Nuremberg Trial” dan “The Tokyo Trial” (1948)135. Pengadilan yang mengadili penjahat perang Jerman dan Jepang ini memperoleh pengakuan secara resmi dari Majelis Umum PBB melalui resolusinya tanggal 11 Desember 1948. Dengan pengakuan tersebut, maka validitas peradilan Nuremberg dan penerapannya pada kemudian hari, tidak akan dipersoalkan lagi. Bahkan pada masa yang akan datang, yurisdiksi peradilan atas pelaku kejahatan perang diperluas mencakup juga kejahatan terhadap kemanusiaan, dan perdamaian, yang dilakukan dalam kaitan peperangan.
KESIMPULAN
Bangsa Indonesia disaat memproklamasikan kemerdekaannya belum mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan yang lengkap. Baru pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan diundangkan UUD 1945 yang memuat aturan-aturan pokok. Untuk mengisi kekosongan hukum, maka Aturan Peralihann UUD 1945 menetapkan berlakunya aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 maka Hukum Pidana (WvS) diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun mempunyai dasar hukum untuk diberlakukan WvS di Indonesia (yaitu aturan peralihan pasal II) namun demikian jelas ini suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi bangsa kita, bagaimanapun hukum yang dibuat oleh Belanda yang notabene adalah bangsa asing, tidak akan bisa mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia secara umum. Usaha untuk mengganti hukum warisan kolonial Belanda bukannya tidak pernah dilakukan. Usaha itu telah dirintis dan terus dilakukan, salahsatunya yang sampai sekarang belum selesai adalah pembaharuan KUHP.
PENUTUP
Demikianlah makalah ini dibuat, dan tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena pemakalah hanyalah manusia biasa yang kurang memahami permasalahan dan sering melakukan kesalahan. Pemakalah sadar ini adalah merupakan proses dalam menempuh pembelajaran, untuk itu pemakalah mengharapkan kritik serta saran yang bisa membangun demi kesempurnaan makalah kami berikutnya. Harapan pemakalah semoga makalah ini dapat dijadikan sebuah kontribusi yang berarti dalam pendidikan kita bersama. Amiin
DAFTAR PUSTAKA
Simposium Pembaharuan hokum, pidana Nasional, yang diselenggarakan oleh BPHN-UNDIP, tgl 28-30 Agustus 1980,SEMARANG
Atmasasmitha, R, 1995. Pengantar Hukum Pidana Internasional, Eresco, Bandung
Andi Hamzah, 1994. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
I. BAB1
PENDAHULUAN
LATAR BLAKANG
Bangsa Indonesia disaat memproklamasikan kemerdekaannya belum mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan yang lengkap. Baru pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan diundangkan UUD 1945 yang memuat aturan-aturan pokok. Untuk mengisi kekosongan hukum, maka Aturan Peralihann UUD 1945 menetapkan berlakunya aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 maka Hukum Pidana (WvS) diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun mempunyai dasar hukum untuk diberlakukan WvS di Indonesia (yaitu aturan peralihan pasal II) namun demikian jelas ini suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi bangsa kita, bagaimanapun hukum yang dibuat oleh Belanda yang notabene adalah bangsa asing, tidak akan bisa mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia secara umum. Usaha untuk mengganti hukum warisan kolonial Belanda bukannya tidak pernah dilakukan. Usaha itu telah dirintis dan terus dilakukan, salahsatunya yang sampai sekarang belum selesai adalah pembaharuan KUHP.
Adapun WvS (selanjutnya disebut KUHP / Kitab Undang-undangHukum Pidana) kemudian diberlakukan dengan UU nomor 1 tahun 1946 yang ditetapkan pada tanggal 26 Pebruari 1946. Adapun bunyi dari pada UU ini adalah: “menimbang, bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan UU hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana yang disesuaikan dengan keadaan sekarang”. Dengan demikian maka UU ini merupakan peraturan peralihan, yang memuat hukum transitoir, yang tampak dalam pasal I, yang menetapkan, “bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hokum pidana yang ada pada tanggal 8 maret 1945”. Pada tanggal tersebut, yang berlaku ialah peraturan hukum pidana Belanda, akan tetapi dalam pasal II Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa, semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh panglima bala tentara Hindia Belanda dicabut, antara lain peraturan hukum pidana yang memuat ancaman pidana, dalam larangan menimbun barang. Sehubungan dengan itu ada juga produk perundang-undangan yang memperbaharui kemudian dimasukkan kedalam pasal-pasal KUHP. Misalnya antara lain, UU No. 20 tahun 1946 yang menambah jenis pidana pokok dengan satu pidana baru yaitu mengenai tentang Pidana Tutupan, UU No. 73 tahun 1958 yang mengadakan beberapa perubahan dalam Bab I buku II KUHP, UU No. 4 tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan. Berdasarkan beberapa UU tersebut kemudian pasal-pasal yang ada didalam KUHP ditambah dan dilengkapi. . Disamping peraturan perundangan tersebut diatas, juga yang merupakan delik khusus adalah pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama setelah peristiwa Timor Timur, permasalahan pelanggaran HAM banyak dibahas oleh para ahli. Selanjutnya dengan mengacu kepada UU nomor 39 tahun 1999 dan UU nomor 26 tahun 2000 (Pengadilan HAM), maka dikenal dua bentuk pelanggaran HAM, yaitu palanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pengertian Pelanggaran HAM terdapat dalam Pasal 1 butir 6 dan pengertian Pelanggaran HAM Berat terdapat dalam penjelasan UU No. 39 tahun 1999 yaitu dalam Pasal 104 ayat 1. Pasal 1 butir 6 menyatakan :Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hokum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
II. Perumusan Masalah dan Pembahasan
Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan, maka
permasalahan yang dirumuskan untuk penyususunan thesis ini adalah :
1. Perkembangan Tanggung Jawab Komando Terhadap pelanggaran
HAM yang berat Dan Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional?
2. Penerapan Tanggung Jawab Komando dalam Kasus-kasus
Pelanggaran Berat HAM di Indonesia?
Pembaharuan Hukum Acara Pidana (HAP) merupakan suatu hal yang harus dilakukan bila pemerintah memilki kemauaan untuk memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Hukum acara pidana dalam KUHAP yang menjadi acuan dasar hukum acara pidana sktoral dilupakan padahal, UU Sektoral hanya memberikan penambahan aturan khusus, sedangkan secara umum tetap mempergunakan KUHAP, mudahnya bila tidak terdapat ketentuan dalam UU Sektoral tersebut maka KUHAP yang menjadi acuan.
Pembaharuan KUHAP sebenarnya telah menjadi kebutuhan, tidak hanya karena UU No 8 Tahun 1981 yang familiar KUHAP saat ini banyak menimbulkan permasalahan seperti pelanggaran HAM orang yang berhadapan dengan hukum pidana, penyiksaan untuk mendapatkan pengakuaan atau informasi, tidak jelasnya sistem peradilan pidana di Indonesia, dan jual beli kewenangan (upaya paksa oleh penegak hukum). Permasalahan tersebut terjadi karena lemahnya kontrol internal dalam sistem peradilan pidana itu sendiri, pra peradilan yang diharapkan menjadi kontrol masyarakat terhadap kekuasaan negara yang begitu besar ternyata hanya menjadi kontrol administrative saja dan bersifat amat sangat pasif. Kontrol hakim / ketua pengadilan sebagai bentuk aplikatif kontrol yudikatif terhadap eksekutif pada sistem peradilan pidana tidak mendapatkan kewenangan yang terlalu besar . Lembaga kontrol pengawas eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial hanya menjadi hiasan semata, karena lemahnya kewenangan yang diberikan kepada mereka.
Upaya pembaharuan hukum acara pidana yang dilakukan oleh Tim Pembaharuan Hukum Acara Pidana dengan mempertimbangkan adanya perubahan sosial, teknologi, transportasi dll serta Konsekuensi Indonesia telah mengesahkan (ratifikasi) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang Kejam, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Semangat pembaharuan KUHAP terus mendapatkan hambatan dari berbagai pihak khususnya dari aparatur penegak hukum itu sendiri
Atas dasar itu penting bagi pemerintah untuk Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik, khususnya untuk penahanan sebelum pengadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
I. Perlindungan Praduga Bersalah
Semua negara di dunia, yang mengakui sebagai negara hukum menerapkan asas praduga tak bersalah. Konstitusional Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, Pasal 11 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya sesuai dengan hukum , dalam pengadilan yang terbuka dimana ia memperoleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk melakukan pembelaanya”
Penahanan sebelum adanya putusan hukum yang final, adalah bentuk penginkaran atas hak asasi manusia dan asas Praduga tidak bersalah. Pembatasan atas hak tersebut selain harus secara jelas dinyatakan oleh Undang-Undang. UU No 8 Tahun 1981 (KUHAP) telah mengatur penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulang tindak pidana. KUHAP memberikan wewenang penuh kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk menentukan apakah tersangka/terdaka ditahan atau tidak dengan pertimbangan subyektif karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, penentuan subyektif tersebut haruslah melihat fakta-fakta yang ada, sehingga menjadi penting penentuan tersangka dapat ditahan atau tidak haruslah diambil oleh pihak yang menjalankan fungsi pengadilan dalam hal ini hakim bukan penyidik atau penuntut umum.
Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik berjanji untuk menghormati dan menjamin aturan dalam kovenan baik dalam aturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan yang diambil
Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Konvensi Hak sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005 secara tegas menyatakan “Siapapun yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan kekuasaan pengadilan” ayat (4) menyatakan “Siapapun yang dirampas kemerdekaanya dengan cara penangkapan, mempunyai hak untuk disidangkan di depan pengadilan, agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya dan memerintahkan pembebasan apabila penahanan tersebut tidak sah menurut hukum”
Ketentuan hukum acara pidana yang saat ini diberlakukan di Indonesia melalui UU No 8 Tahun 1981 tidak mengakomodir ketentuan tersebut, Penyidik untuk dan atas kepentingannya dapat melakukan penahanan terhadap orang yang diduga dengan bukti permulaan yang cukup selama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari . Sedangkan Penuntut umum dapat menahan tersangka selama 20 hari. Sehingga Hakim sebagai pemegang kewenangan yudikatif baru mengetahui kondisi tersangka yang ditahan ketika pembacaan dakwaan.
Bila ketentuan tersebut tetap dilanggengkan oleh Pembuat Undang-Undang yang melakukan pembaharuan hukum acara pidana, maka Negara Indonesia dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui regulasi yang dikeluarkan.
3. Perkembangan Tanggung Jawab Komando Terhadap pelanggaran
HAM yang berat Dan Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional.
Di bawah ini dijelaskan beberapa praktik penerapan tanggung jawab komando yang terjadi pada masa awal perkembangan doktrin ini. Beberapa contoh kasus yang terjadi pada masa awal perkembangan doktrin ini, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasisituasi yang memungkinkan seorang komandan atau atasan dimintai pertanggungjawaban karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bawahannya. Dari ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab komando serta proses hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus tersebut, akan dikemukakan elemen-elemen pokok yang menjadi dasar penentuan kesalahan seorang komandan atau atasan atas dasar doktrin tanggung jawab komando atau tanggung jawab atasan. Mulanya, Raja Charles Vll dari Perancis di Orleans pada tahun 1493 mengeluarkan perintah yang tegas berkaitan dengan doktrin tanggung jawab komando. Perintah tersebut menyatakan: ”Raja memerintahkan bahwa setiap kapten atau letnan bertanggung jawab atas
penyimpangan, tindakan buruk dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kompinya, dan setelah ia menerima suatu pengaduan mengenai adanya kesalahan atau penyimpangan tersebut, ia membawa pelakunya ke pengadilan sehingga pelakunya dihukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Jika ia tidak melakukan hal itu atau menutupi kesalahan atau tidak mengambil tindakan, atau jika, karena kelalainnya atau kesengajaannya pelaku kejahatan melarikan diri sehingga terhindar dari hukuman, kapten tersebut harus dianggap bertanggung jawab atas kejahatan tersebut seolah-olah ia telah melakukan sendiri kejahatan itu dan harus dihukum sama seperti yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan”. Beberapa aspek penting mengenai doktrin tanggung jawab komando yang terdapat dalam perintah raja Charles tersebut adalah: pertama, komandan bertanggung jawab untuk mengendalikan perilaku termasuk cara bertindak yang dilaksanakan oleh bawahannya agar tidakmenyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku; kedua, komandan berkewajiban untuk memproses setiap bawahannya yang terlibat sebagai pelaku kejahatan secara hukum; ketiga, jika komandan karena kelalaian atau kesengajaan membiarkan kejahatan terjadi dan tidak melakukan 56 kedua hal tersebut di atas, maka ia bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh prajurit bawahannya. 75 Selanjutnya, perkembangan doktrin tanggung jawab komando ini, diberlakukan oleh penguasa Austria (the archduke of austria) yang pada tahun 1474 ia mengadili Peter Von Hagenbach, yang telah memimpin rangkaian kejahatan selama ia berkuasa untuk kepentingan Charles dari Burgundy di wilayah Upper Rhine yang baru ditaklukkan. Ia dipersalahkan karena melakukan kejahatan perkosaan, pembunuhan, melanggar sumpah dan kejahatan terhadap Tuhan dan manusia (the law of god and man).76 Dalam pembelaannya di depan pengadilan, Peter menyatakan tindakan tersebut dilakukan atas dasar perintah atasan. Namun pengadilan menolak pembelaan atas dasar perintah atasan tersebut dan dalam putusannya menyatakan Peter bersalah melakukan kejahatan yang semestinya ia berkewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Putusan dalam kasus Peter ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa: ”negara dan pejabat yang berkuasa bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah kekuasaannya, jika mereka mengetahui kejahatan tersebut dan tidak melakukan pencegahan padahal mereka dapat dan harus melakukan hal itu”.
Penerapan Tanggung Jawab Komando dalam Kasus-kasus
Pelanggaran Berat HAM di Indonesia.
1. Pengaturan Tanggung Jawab Komando dalam Hukum Positif Hukum hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 mengatur pertanggungjawaban komandan militer sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 42. Di dalam system hukum pidana Indonesia juga dikenal apa yang disebut sebagai pertanggungjawaban pidana. Mengenai istilah ini di dalam bahasa Belanda terdapat tiga kata yang sinonim, yaitu aanspraakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar. Orangnya yang aanspraakelijk atau verantwoordelijk, sedangkan toerekenbaar bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang, biasanya pengarang lain memakai istilah toerekenbaar132. Dalam hal pertanggungjawaban pidana dikenal beberapa pembatasan, yang tidak semua orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP yang mengatur tentang pengecualian pelaku dari 132 Hamzah, S, 1991. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 108 mengutip Pompe 90 pertanggungjawaban pidana. Namun lain halnya dengan pertanggungjawaban di lingkup militer, seorang komandan tidak dapat bebas dari pertanggungjawaban pidana, apabila ia mengetahui bahwa anak buanya telah atau akan melakukan kejahatan yang berhubungan dengan tugas mereka dan sepanjang perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan jika ia tidak mencegah/bertindak dan hanya membiarkan/tidak melakukan sesuatu (omission) maka komandan tersebut tetap dipertanggungjawabkan, karena adanya hubungan khusus, antara komandan (superior) dan bawahan (inferior). Berdasarkan precedents/case law hubungan atasan dan bawahan dapat didasari atas dasar de jure dan de facto. De jure ialah pengangkatan seseorang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hierarki seorang atasan dengan bawahan beserta tugas masing-masing, de facto merupakan hubungan atasan bawahan dalam kenyataannya di lapangan antara lain bagaimana pandangan unit kerja terhadap atasan. Dalam kasus yang diadili oleh pengadilan pidana internasional (ICTR dan ICTY) para terdakwa yang didakwa sebagai seorang atasan oleh karena secara de facto dan de jure adalah kasus akeyashu, yang didakwa karena mempunyai otoritas de Jure dan de facto baik terhadap golongan sipil, maupun polisi dan tentara. Mengenai pertanggungjawaban di lingkup militer sebenarnya bermula dari yurisprudensi yang terkenal, yaitu berkenaan dengan kasuskasus setelah Perang Dunia II terhadap para penjahat perang NAZI Jerman dan Fasis Jepang, yang dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindakan semasa peperangan melalui suatu pengadilan yang dikenal dengan nama “The Nuremberg Trial” dan “The Tokyo Trial” (1948) . Pengadilan yang mengadili penjahat perang Jerman dan Jepang ini memperoleh pengakuan secara resmi dari Majelis Umum PBB melalui resolusinya tanggal 11 Desember 1948. Dengan pengakuan tersebut, maka validitas peradilan Nuremberg dan penerapannya pada kemudian hari, tidak akan dipersoalkan lagi. Bahkan pada masa yang akan datang, yurisdiksi peradilan atas pelaku kejahatan perang diperluas mencakup juga kejahatan terhadap kemanusiaan, dan perdamaian, yang dilakukan dalam kaitan peperangan. Kasus-kasus yang diputus oleh pengadilan militer Internasional (IMT) tersebut antara lain kasus terhadap penjahat perang jepang Jenderal Tomoyuki Yamashita, yang dijatuhi hukuman mati karena terbukti bahwa ia sebagai seorang komandan tertinggi/gubernur militer Jepang di Philipina telah gagal mengawasi bawahannya yang melakukan kejahatan-kejahatan perang dan kekejaman lainnya yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum internasional. Meskipun Yamashita dalam pembelaannya mengatakan bahwa ia tidak mengetahui perbuata pasukannya karena ia kehilangan komunikasi karena jaraknya ratusan mil dari tempatnya, namun Yamashita tetap dipersalahkan sebagai atasan dan bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya yang melakukan kejahatan perang. Kasus jenderal Tomoyuki Yamashita merupakan contoh dalam pertanggungjawabab secara strict liability. Charter International Military Tribunal Nuremberg Trial ini penting artinya karena memuat Prinsip baru yang diterapkan untuk Mahkamah Nuremberg dan Mahkamah Tokyo, antara lain tentang pertanggungjawaban pribadi dan asas retroaktif. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam Statuta ICTY, ICTR, serta pengadilan di Indonesia yaitu dalam UU tentang Pengadilan HAM. Mahkamah Nuremberg juga mengemukakan bahwa prinsip pertanggungjawaban individu dan penghukuman bagi kejahatan-kejahatan internasional, merupakan dasar utama dari hukum pidana internasional. Prinsip ini merupakan warisan abadi yang disumbangkan oleh Piagam dan Putusan Nuremberg (Nuremberg Charter and Judgment) yang meletakkan konsep bagi larangan kejahatan-kejahatan berdasarkan hukum internasional dengan menjamin bahwa individu-individu yang melakukan kejahatan perang akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Karnasudirdja, peradilan Nuremberg dan Tokyo telah menciptakan konsep-konsep hokum internasional baru yang penting dan kemudian diakui oleh PBB dan 93 diadopsi oleh hukum internasional serta dilaksanakan oleh Pengadilan Pidana Internasional lainnya . Lebih lanjut lagi tentang pertanggungjawaban individu ini, Pasal 8 dari Piagam Mahkamah Nuremberg mengatur bahwa perintah dari pemerintah atau atasannya tidak akan membebaskan seseorang dari tanggungjawab pidana, tetapi mungkin dapat dipertimbangkan dalam meringankan hukuman, jika mahkamah menentukan bahwa keadilan amat disyaratkan. Dengan demikian ini berarti bahwa perintah jabatan atau atasan tidak dapat dijadikan alasan penghapus hukuman. Mahkamah Nuremberg juga memutuskan bahwa tiap individu mempunyai kewajiban internasional yang melebihi kepatuhan atas kewajiban-kewajiban nasional yang dipatuhi oleh individu negara. Ini merupakan pemikiran revolusioner yang membatasi kedaulatan mutlak tiap negara, bukan oleh hukum yang ditujukan kepada negara, tetapi oleh hukum yang ditujukan kepada individu. Prinsip tanggungjawab individu tersebut didasarkan pada ketentuan supremasi hukum yang ditetapkan berdasarkan ilham yang ada dalam the Common Law. Dalam ketentuan hukum tersebut dikemukakan bahwa menteri-menteri atau pembantu Raja akan bertanggungjawab secara hukum atas tindakan yang dilakukannya, dan ia tidak dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan alasan bahwa ia bertindak untuk patuh kepada perintah Raja. Mahkamah Nuremberg selanjutnya menyimpulkan Mengenai pertanggungjawaban di lingkup militer sebenarnya bermula dari yurisprudensi yang terkenal, yaitu berkenaan dengan kasus kasus setelah Perang Dunia II terhadap para penjahat perang NAZI Jerman dan Fasis Jepang, yang dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindakan semasa peperangan melalui suatu pengadilan yang dikenal dengan nama “The Nuremberg Trial” dan “The Tokyo Trial” (1948)135. Pengadilan yang mengadili penjahat perang Jerman dan Jepang ini memperoleh pengakuan secara resmi dari Majelis Umum PBB melalui resolusinya tanggal 11 Desember 1948. Dengan pengakuan tersebut, maka validitas peradilan Nuremberg dan penerapannya pada kemudian hari, tidak akan dipersoalkan lagi. Bahkan pada masa yang akan datang, yurisdiksi peradilan atas pelaku kejahatan perang diperluas mencakup juga kejahatan terhadap kemanusiaan, dan perdamaian, yang dilakukan dalam kaitan peperangan.
KESIMPULAN
Bangsa Indonesia disaat memproklamasikan kemerdekaannya belum mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan yang lengkap. Baru pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan diundangkan UUD 1945 yang memuat aturan-aturan pokok. Untuk mengisi kekosongan hukum, maka Aturan Peralihann UUD 1945 menetapkan berlakunya aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 maka Hukum Pidana (WvS) diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun mempunyai dasar hukum untuk diberlakukan WvS di Indonesia (yaitu aturan peralihan pasal II) namun demikian jelas ini suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi bangsa kita, bagaimanapun hukum yang dibuat oleh Belanda yang notabene adalah bangsa asing, tidak akan bisa mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia secara umum. Usaha untuk mengganti hukum warisan kolonial Belanda bukannya tidak pernah dilakukan. Usaha itu telah dirintis dan terus dilakukan, salahsatunya yang sampai sekarang belum selesai adalah pembaharuan KUHP.
PENUTUP
Demikianlah makalah ini dibuat, dan tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena pemakalah hanyalah manusia biasa yang kurang memahami permasalahan dan sering melakukan kesalahan. Pemakalah sadar ini adalah merupakan proses dalam menempuh pembelajaran, untuk itu pemakalah mengharapkan kritik serta saran yang bisa membangun demi kesempurnaan makalah kami berikutnya. Harapan pemakalah semoga makalah ini dapat dijadikan sebuah kontribusi yang berarti dalam pendidikan kita bersama. Amiin
DAFTAR PUSTAKA
Simposium Pembaharuan hokum, pidana Nasional, yang diselenggarakan oleh BPHN-UNDIP, tgl 28-30 Agustus 1980,SEMARANG
Atmasasmitha, R, 1995. Pengantar Hukum Pidana Internasional, Eresco, Bandung
Andi Hamzah, 1994. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.